
Apakah Digitalisasi Pendidikan Dosen dan Mahasiswa Sudah Siap?
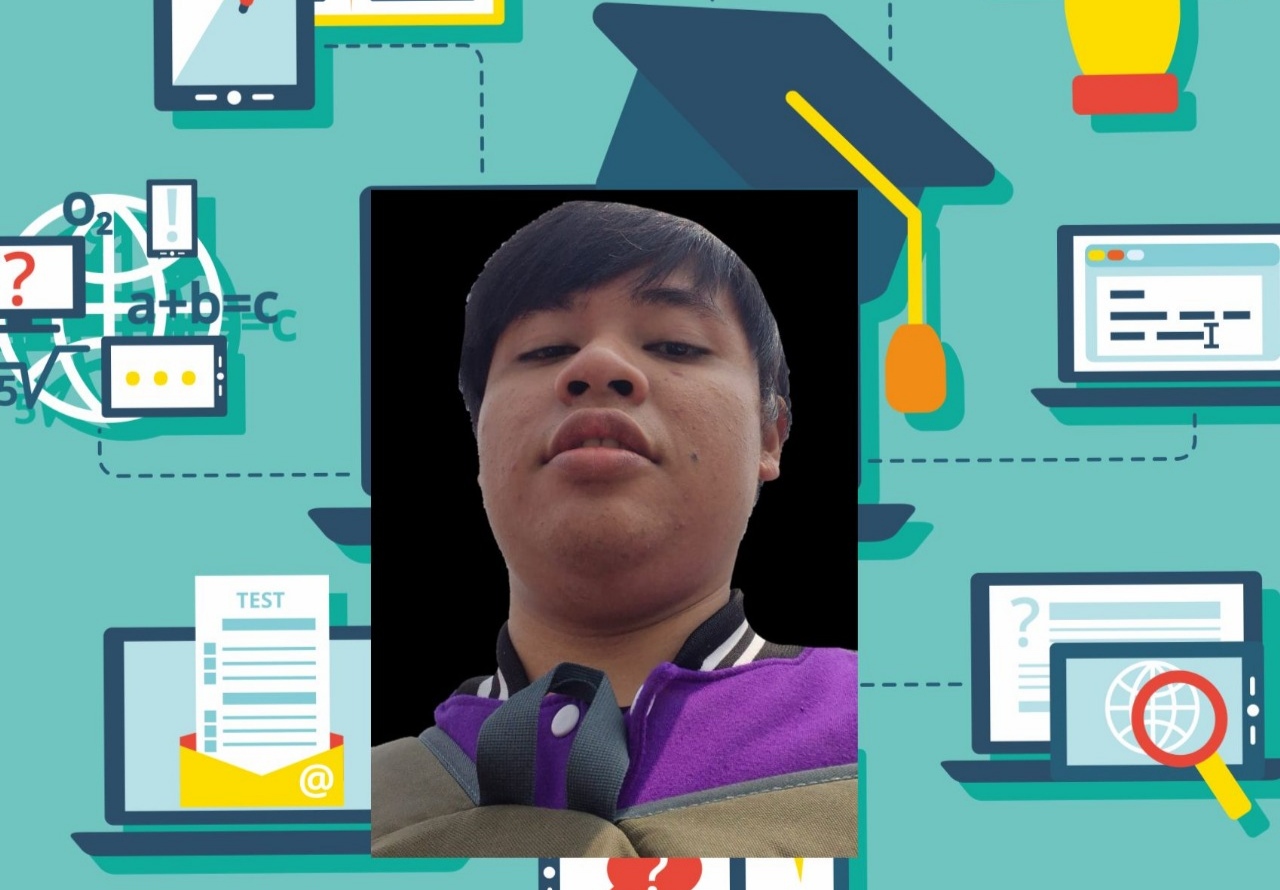
AXIALNEWS.id | Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Setelah pandemi COVID-19, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah dosen dan mahasiswa di Indonesia benar-benar sudah siap menghadapi digitalisasi pendidikan?
Era Baru Pembelajaran
Digitalisasi pendidikan menawarkan banyak kemudahan. Proses belajar kini tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Mahasiswa bisa mengakses materi kuliah melalui Learning Management System (LMS), berdiskusi lewat forum daring, dan mengikuti kelas virtual dengan dosen dari berbagai daerah. Bahkan, berbagai platform seperti Coursera, Ruang Guru, hingga Kampus Merdeka membuka peluang belajar lintas kampus dan lintas negara.
Namun, di balik semua kemudahan itu, ada tantangan besar yang belum terselesaikan. kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Tidak semua kampus memiliki fasilitas digital yang memadai. Beberapa dosen masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi, sementara sebagian mahasiswa menghadapi kendala akses internet atau perangkat. Akibatnya, kualitas pembelajaran digital seringkali tidak maksimal.
Tantangan bagi Dosen dan Mahasiswa
Bagi dosen, digitalisasi pendidikan bukan sekadar memindahkan materi kuliah ke PowerPoint dan mengajar lewat Zoom. Lebih dari itu, dibutuhkan kemampuan baru seperti mengelola kelas virtual, membuat konten interaktif, serta mengevaluasi pembelajaran secara daring. Banyak dosen yang sebelumnya terbiasa dengan metode konvensional kini harus belajar menjadi Edukator Digital.
Sementara bagi mahasiswa, digitalisasi pendidikan menuntut kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak ada lagi dosen yang selalu mengingatkan tugas secara langsung. Mahasiswa dituntut aktif mencari sumber belajar, mengatur waktu, dan menghindari distraksi dari media sosial. Sayangnya, sebagian mahasiswa justru terjebak dalam kebiasaan pasif seperti hanya hadir di kelas daring tanpa benar-benar memahami materi.
Fenomena “mahasiswa Zoom tapi tidak belajar” menjadi gambaran nyata bahwa digitalisasi belum otomatis membuat pendidikan lebih efektif. Tanpa kesadaran belajar dan etika digital, kemajuan teknologi hanya menjadi formalitas.
Kesenjangan Digital yang Nyata
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kesenjangan digital antar daerah. Di kota-kota besar, mahasiswa mungkin bisa mengikuti perkuliahan online dengan lancar. Namun di daerah terpencil, akses internet masih menjadi kendala serius. Bahkan ada mahasiswa yang harus mencari sinyal di bukit demi mengikuti ujian daring. Kondisi ini menandakan bahwa digitalisasi pendidikan masih belum sepenuhnya inklusif.
Selain itu, keterbatasan literasi digital juga menjadi masalah tersendiri. Tidak semua dosen dan mahasiswa memahami etika penggunaan sumber digital, hak cipta, serta keamanan data pribadi. Akibatnya, plagiarisme dan penyalahgunaan informasi digital semakin marak.
Peluang di Balik Tantangan
Meski penuh tantangan, digitalisasi pendidikan juga membuka peluang besar. Mahasiswa kini bisa belajar dengan lebih fleksibel, berjejaring secara global, dan mengembangkan soft skill digital seperti komunikasi daring dan kolaborasi virtual. Dosen pun dapat memperluas pengaruhnya melalui publikasi digital, webinar, atau kanal edukatif di media sosial.
Beberapa perguruan tinggi mulai berinovasi dengan hybrid learning yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena tetap menjaga interaksi sosial, sambil memanfaatkan keunggulan teknologi. Jika dikembangkan secara serius, model ini bisa menjadi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia.
Menuju Kesiapan Digital yang Nyata
Untuk benar-benar siap menghadapi era digital, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, peningkatan literasi digital bagi dosen dan mahasiswa harus menjadi prioritas. Pelatihan penggunaan teknologi pembelajaran, keamanan data, serta etika digital perlu diadakan secara rutin.
Kedua, pemerataan infrastruktur digital harus diperkuat, terutama di wilayah luar Jawa. Pemerintah, kampus, dan sektor swasta perlu bekerja sama memperluas akses internet dan penyediaan perangkat belajar. Pendidikan digital tidak akan berhasil jika hanya bisa diakses sebagian kecil masyarakat.
Ketiga, pembelajaran digital harus berorientasi pada kualitas, bukan sekadar formalitas. Artinya, kampus harus mampu menciptakan sistem evaluasi dan interaksi yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti interaksi manusia.
Penutup
Digitalisasi pendidikan memang tidak bisa dihindari. Namun kesiapan manusia jauh lebih penting daripada sekadar kecanggihan alat. Dosen dan mahasiswa harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Pada akhirnya, digitalisasi pendidikan bukan hanya soal siapa yang paling melek teknologi, tetapi siapa yang paling mau belajar. Karena di era serba cepat ini, mereka yang tidak mau beradaptasi bukan hanya tertinggal, tetapi bisa hilang dari peta peradaban pendidikan itu sendiri.(*)
Penulis: Muhammad Rasyid Zafransyah, Mahasiswa Universitas Tazkia.









